Tugas Softskill
Resensi film daun di atas bantal
Potret
muram kehidupan jalananan la Kancil, Heru, dan Sugeng dalam film
semi-dokumenter ‘Daun di Atas Bantal’ selayaknya menjadi tamparan telak bagi siapa yang merasa tertampar. Kepada merekalah sang kehidupan tidak perlu
merasa malu menampilkan wajah terkejamnya secara telanjang. Saling pukul,
saling maki, mencuri, ngelem
(menghirup lem Aica Aibon yang memabukkan), makan melalui lubang, mengintip
perempuan ganti baju, onani sambil menyaksikan film biru dari belakang layar,
mencuci muka dengan air pel stasiun, seolah telah menjadi kawan akrab mereka.
Seakrab peniti-peniti yang menghiasi bibir Heru.
Tidak perlu
heran. Tidak perlu mengernyitkan dahi sedemikian rupa. Siapa saja boleh menilai
hidup semacam itu adalah tidak wajar. Toh, wajar tidak wajar adalah penilaian
yang pilih kasih. Dan, menilai, pada dasarnya adalah membandingkan.
Kepada
mereka, paling tidak ada dua penilaian umum yang muncul dengan segera dari
masyarakat di luar komunitas jalanan. Yang pertama adalah iba. Yang kedua
adalah rasa terganggu atau terusik. Atau, campuran kedua unsur tersebut. Ada
pula yang biasa aja, tidak berkomentar apa-apa, alias cuek bebek saja.
Munculnya
penilaian tersebut dapat diibaratkan “cermin”. Dengan memaksakan standar diri
untuk menilai sesuatu di luar dirinya, memperlihatkan seperti apa diri sang
penilai itu sendiri.Rasa iba timbul karena masyarakat terbiasa dengan suatu standar kenyamanan yang lebih tinggi. Paling tidak, orang tidak perlu berebut bantal bekas kursi sobek untuk alas tidurnya. Rasa iba seakan ingin menegaskan bahwa masyarakat yang merasa iba itu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada anak jalanan yang dijatuhi iba. Rasa iba yang terdengar mulia itu terjebak menjadi kesombongan borjuis yang merendahkan.
Di
sisi lain, masyarakat akan melihat sisi ‘rusak’ mereka. Masyarakat yang
terbiasa dengan aturan boleh saja menilai mereka tidak tahu aturan. Masyarakat
boleh protes atau mengeluh mengenai sikap mereka yang melempari kaca sebuah
tempat penukaran uang, makan tanpa bayar, mengganjal roda bianglala di pasar
malam (membahayakan penumpang),
tidak pernah mandi atau mengganti pakaian, dan segala hal serba ‘sembarangan’ lainnya.
Namun,
aturan-aturan tersebut milik siapa? Apakah anak jalanan merasa ikut memiliki
aturan-aturan tersebut? Apakah mereka ikut bersepakat bahwa aturan-aturan
tersebut adalah ‘demi kepentingan mereka sendiri’ juga?
Ketika
aturan-aturan yang ada sengaja meniadakan mereka, apakah berarti mereka tidak
boleh ikut bermasyarakat? Ketika aturan-aturan tidak aspiratif bagi kepentingan
mereka – bahkan secara kasat mata mematikan atau membunuh mereka – bagaimana
mungkin mereka mematuhinya? Dalam hal ini, dapatkah masyarakat bilang bahwa
mereka anarkis? Ataukah justru yang membuat aturan itulah yang anarkis?Arief Budiman mempunyai ilustrasi yang menarik:
Ketika kekuasaan kehilangan keabsahannya, ia sama saja dengan kawanan penjahat yang memaksa anggotanya untuk mengikuti kehendaknya dengan ancaman kekerasan.
Meskipun
pada dasarnya sama-sama melanggar aturan, namun dengan dalih bahwa kekuasaannya
absah, sang penguasa tentu berkelit dari tuduhan anarkis, melanggar aturan,
entah dengan alasan “harus”, atau “demi kepentingan bersama”, alasan apa saja
bisalah dibuat ….
Padahal,
keabsahan itu sendiri datangnya dari mana? Bila keabsahan itu datangnya dari
rakyat, maka sesungguhnya masyarakatlah yang berhak menilai anarkis tidaknya
sesuatu, termasuk bila yang anarkis itu adalah sang pengemban ‘kekuasaan yang
sah’ itu sendiri. Namun, ternyata, kekuasaan ‘sah’ itulah yang menjadi penentu.
Berkaitan
dengan pembicaraan mengenai aturan-aturan dan keabsahan, nama Sokrates patut disimak.
Dalam satu perkataannya, Sokrates pernah berkata bahwa ia adalah seekor lalat
pengganggu. Maksudnya, lalat pengganggu bagi yang berkuasa. Selayaknya
pengganggu, bagi sang penguasa, orang-orang seperti dia dirasa sepantasnya
Mungkin perumpamaan tersebut sesuai pula untuk anak jalanan. Fenomena anak jalanan menjadi kenyataan yang cukup mengganggu bagi pemimpin dan penguasa, karena masyarakat yang solider menuntut kewajiban sang penguasa. Sampai kapan masyarakat akan menerima keberadaan anak-anak di jalanan dan diam-diam mengutuk diri karena yang bisa dilakukan hanya memberi sekeping dua keping rupiah, entah ke mana perginya dan entah seperti apa nasib mereka dan entah kapan ada perubahan dalam hal ini :-(
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, demikian kata UUD ’45.
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum… begitu bunyi Pembukaan (Preambule) UUD 45.
Anak jalanan hanya boleh mendengar tapi tidak boleh ikut menikmati. Indah perkataan tanpa realisasi. Secara teoritis, untuk menuntut perlakuan/perlindungan yang lebih baik, anak jalanan dan orang-orang yang peduli perlu mengorganisasikan diri. Tidak bisa hanya dengan seruan moral. Tapi, yang berlaku adalah hukum rimba, cengkeraman sedemikian berlapis, yang menyebabkan begitu sulitnya sebuah “perjuangan bersama” kaum jalanan.
Terowongan kereta api itu menjadi saksi kematian Kancil ….
Selanjutnya, Heru dan Sugeng menyusul. Keduanya dibunuh. Heru dibunuh oleh mafia asuransi yang memanfaatkan status anak jalanan yang tidak memiliki identitas resmi semacam KTP. Sugeng menjadi korban perseteruan geng atau kelompok preman. Bahkan, sekadar mengubur mayat Sugeng saja susah bukan main, karena pemakaman-pemakaman menolak menyediakan tempat bagi orang yang tidak jelas identitasnya.
Binatang saja dikubur….
demikian lolongan Asih, ibu asuh ketiga anak jalanan tersebut. Masa‘ manusia tidak? Kalau begini, siapa yang tidak manusiawi?
Tiga
kejadian yang merenggut nyawa Kancil, Heru, dan Sugeng begitu saja – seolah
nyawa mereka tidak ada harganya – menunjukkan betapa miris posisi mereka dalam
bangunan struktur sosial.
Dalam struktur
yang menindas selalu ada korban. Kali ini, si Lalat Pengganggu tentu saja kalah
oleh sang Raksasa Penindas.Hukum harus tegas dan tidak ada penguasa di negeri ini. seperti halnya yang tercantum di uud 1945 !!
Sekian dari saya semoga bermanfaat lebih dan kurang saya mohon maaf.
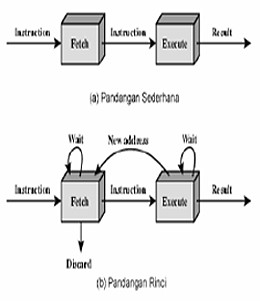
Komentar
Posting Komentar