Tugas softskill III
Tugas Softfkill
Tawuran Antar Mahasiswa
Berpijak pada realitas empiris yang ada, menunjukkan bahwa tawuran mahasiswa seolah telah menjadi bagian integral dari kehidupan kampus yang sulit dipisahkan secara dikotomis. Bahkan dengan beberapa pengecualian kondisinya sudah nyaris menyerupai ungkapan “di mana ada gula di situ ada semut”, di mana ada kampus di situ ada tawuran. Sungguh sangat memperihatinkan sekaligus ironis memang, karena tindakan tidak terpuji ini dipraktekkan di lingkungan ilmiah yang dihuni oleh insan-insan yang menamakan dirinya (dikenal) sebagai kaum intelektual. Fenomena sosial menarik lainnya sekitar kehidupan kampus, yakni suburnya solidaritas mahasiswa yang berbasis etnik.
Akibatnya, timbullah pengkotak-kotakan secara separatis mahasiswa berdasarkan etnisitas yang tidak jarang menjadi penyubur bagi tumbuhnya benih konflik. Sebuah contoh menarik yakni suatu ketika terjadi perkelahian antardua orang mahasiswa yang hanya secara kebetulan berbeda asal daerah, lalu berkembang menjadi persoalan kelompok. Pemicunya, antara lain karena ketika seseorang bertanya siapa yang berkelahi, maka jawaban yang mengemuka adalah anak Bone melawan anak Luwu. Demikian pula jawaban dapat berupa anak fakultas A melawan anak fakultas B. Padahal yang seharusnya terjadi adalah jawaban itu berbunyi: “yang berkelahi itu adalah sesama mahasiswa UNM, sesama mahasiswa Unhas, sesama mahasiswa UMI, dan sebagainya”.
Kenyataan tersebut merupakan pertanda bahwa demikian sulitnya tumbuh dan tercipta sebuah “nasionalisme” dalam wujud solidaritas berbasis kampus. Akibatnya, di tengah masih seringnya terjadi aksi tawuran mahasiswa, maka sebagai warga kampus tentu harus ikhlas menelan pil pahit dalam bentuk kritikan atas eksistensi kampus sebagai lembaga ilmiah. Sebut saja antara lain berupa lahirnya anekdot: “sebodoh-bodohnya tukang becak, belum pernah terjadi pembakaran atas becak mereka saat terjadi perkelahian, sementara para mahasiswa ketika berkelahi justru membakar kampusnya”. Bahkan satu cerita lucu lagi yang muncul, yakni: “dulu katanya mahasiswa yang sering menonton dari dalam kampus tukang becak yang berkelahi di luar (di jalan), sedangkan sekarang justru para tukang becak yang menonton dari luar mahasiswa yang berkelahi di dalam kampus”.
Munculnya tawuran mahasiswa memang telah membuka ruang dan peluang kepada masyarakat untuk menggugat eksistensi kampus. Lalu seperti apa motif, bentuk, dan sumber terjadinya konflik antar mahasiswa?, dan bagaimana pula solusi alternative yang perlu ditawarkan?.
Uraian akan hal tersebut Yakni :
(1) Konflik dalam bentuk kekerasan di dalam kampus adalah suatu realitas sosial, sehingga yang perlu dilakukan adalah mencegah agar perilaku kekerasan tersebut tidak berlanjut;
(2) Untuk menanggulangi perilaku kekerasan, maka yang terpenting adalah memahami dan menganalisis akar persoalan terjadinya perilaku kekerasan melalui studi dinamika konflik sosial sehingga dapat dikembangkan suatu upaya penanggulangan terhadap perilaku kekerasan tersebut;
(3) Mahasiswa yang menempuh pendidikan di dalam kampus mempunyai muatan kepentingan yang homogen secara umum yaitu terciptanya masyarakat akademik dengan kematangan berpikir dan berperilaku. Kematangan berpikir dan berperilaku adalah ciri kehidupan di dalam kampus, tetapi tidak dapat dipungkiri dari realitas sosial dalam kampus sering muncul konflik sosial dalam bentuk perilaku kekerasan.
Seharusnya sebagai seseorang mahasiswa kita harus lebih dewasa dalam berfikir, untuk apa melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti tawuran, belajar dan berkarya merupakan tugas utama seorang mahasiswa, jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan seorang mahasiswa yang baik tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu.
mungkin kegiatan-kegiatan antar mahasiswa dapat membuat mahasiswa tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. kegiatan-kegiatan perlombaan2 misalnya. atau study banding antar universitas.
Konflik Pemilu
Konflik yang terjadi di pilkada langsung sering dijadikan dasar sebagian dewan yang mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Padahal jika dibandingkan dengan jumlah penyelenggaraan pilkada senasional, persentase terjadinya konflik sangat sedikit. Kalau pun terjadi konflik itu disebabkan elite partai dan pasangan calon yang tak menerima keterpilihan pasangan calon lain.
Pada konferensi pers “Mengecam dan Menolak Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD” yang diselenggarakan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (5/9), pakar pemilu, Sri Budi Eko Wardani mengatakan, alasan konflik tinggi di pilkada tak tepat. Direktur eksekutif Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) ini membandingkan jumlah pilkada se-Indonesia yang ternyata persentase terjadinya konflik sangat kecil. Konflik yang terjadi pun lebih berdasar para elite yang tak terpilih tak bisa menerima keterpilihan kandidat lain.
“Seharusnya perbaikan pemilu nasional dan daerah lebih banyak pada pembahasan perbaikan partai. Yang didorong harusnya reformasi partai untuk terbuka. Tertutupnya partai pun menjadikan biaya pilkada sangat fantasitis termasuk di dalamnya harga pencalonan kepala daerah di dalam partai atau koalisi partai,” jelas Sri.
Pakar tata negara, Refly Harun menilai soal konflik merupakan hal yang harusnya tak diselesaikan dengan cara tak lebih demokratis. Direktur eksekutif Correct ini menilai sikap DPR yang ingin mengembalikan pilkada langsung menjadi melalui DPRD sebagai permasalahan konstitusional bagi Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan otonomi daerah.
Refly menilai, rakyat yang berdaulat melalui pemilihan langsung semakin dewasa menyikapi hasil pemilu. Ia merujuk pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Menurutnya, jika elite partai dan paslon yang tak terpilih bisa menerima keterpilihan paslon lain, konflik horizontal tak akan besar bahkan tak ada.
Tawuran Antar Mahasiswa
Berpijak pada realitas empiris yang ada, menunjukkan bahwa tawuran mahasiswa seolah telah menjadi bagian integral dari kehidupan kampus yang sulit dipisahkan secara dikotomis. Bahkan dengan beberapa pengecualian kondisinya sudah nyaris menyerupai ungkapan “di mana ada gula di situ ada semut”, di mana ada kampus di situ ada tawuran. Sungguh sangat memperihatinkan sekaligus ironis memang, karena tindakan tidak terpuji ini dipraktekkan di lingkungan ilmiah yang dihuni oleh insan-insan yang menamakan dirinya (dikenal) sebagai kaum intelektual. Fenomena sosial menarik lainnya sekitar kehidupan kampus, yakni suburnya solidaritas mahasiswa yang berbasis etnik.
Akibatnya, timbullah pengkotak-kotakan secara separatis mahasiswa berdasarkan etnisitas yang tidak jarang menjadi penyubur bagi tumbuhnya benih konflik. Sebuah contoh menarik yakni suatu ketika terjadi perkelahian antardua orang mahasiswa yang hanya secara kebetulan berbeda asal daerah, lalu berkembang menjadi persoalan kelompok. Pemicunya, antara lain karena ketika seseorang bertanya siapa yang berkelahi, maka jawaban yang mengemuka adalah anak Bone melawan anak Luwu. Demikian pula jawaban dapat berupa anak fakultas A melawan anak fakultas B. Padahal yang seharusnya terjadi adalah jawaban itu berbunyi: “yang berkelahi itu adalah sesama mahasiswa UNM, sesama mahasiswa Unhas, sesama mahasiswa UMI, dan sebagainya”.
Kenyataan tersebut merupakan pertanda bahwa demikian sulitnya tumbuh dan tercipta sebuah “nasionalisme” dalam wujud solidaritas berbasis kampus. Akibatnya, di tengah masih seringnya terjadi aksi tawuran mahasiswa, maka sebagai warga kampus tentu harus ikhlas menelan pil pahit dalam bentuk kritikan atas eksistensi kampus sebagai lembaga ilmiah. Sebut saja antara lain berupa lahirnya anekdot: “sebodoh-bodohnya tukang becak, belum pernah terjadi pembakaran atas becak mereka saat terjadi perkelahian, sementara para mahasiswa ketika berkelahi justru membakar kampusnya”. Bahkan satu cerita lucu lagi yang muncul, yakni: “dulu katanya mahasiswa yang sering menonton dari dalam kampus tukang becak yang berkelahi di luar (di jalan), sedangkan sekarang justru para tukang becak yang menonton dari luar mahasiswa yang berkelahi di dalam kampus”.
Munculnya tawuran mahasiswa memang telah membuka ruang dan peluang kepada masyarakat untuk menggugat eksistensi kampus. Lalu seperti apa motif, bentuk, dan sumber terjadinya konflik antar mahasiswa?, dan bagaimana pula solusi alternative yang perlu ditawarkan?.
Uraian akan hal tersebut Yakni :
(1) Konflik dalam bentuk kekerasan di dalam kampus adalah suatu realitas sosial, sehingga yang perlu dilakukan adalah mencegah agar perilaku kekerasan tersebut tidak berlanjut;
(2) Untuk menanggulangi perilaku kekerasan, maka yang terpenting adalah memahami dan menganalisis akar persoalan terjadinya perilaku kekerasan melalui studi dinamika konflik sosial sehingga dapat dikembangkan suatu upaya penanggulangan terhadap perilaku kekerasan tersebut;
(3) Mahasiswa yang menempuh pendidikan di dalam kampus mempunyai muatan kepentingan yang homogen secara umum yaitu terciptanya masyarakat akademik dengan kematangan berpikir dan berperilaku. Kematangan berpikir dan berperilaku adalah ciri kehidupan di dalam kampus, tetapi tidak dapat dipungkiri dari realitas sosial dalam kampus sering muncul konflik sosial dalam bentuk perilaku kekerasan.
Seharusnya sebagai seseorang mahasiswa kita harus lebih dewasa dalam berfikir, untuk apa melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti tawuran, belajar dan berkarya merupakan tugas utama seorang mahasiswa, jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan seorang mahasiswa yang baik tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu.
mungkin kegiatan-kegiatan antar mahasiswa dapat membuat mahasiswa tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. kegiatan-kegiatan perlombaan2 misalnya. atau study banding antar universitas.
Konflik Pemilu
Konflik yang terjadi di pilkada langsung sering dijadikan dasar sebagian dewan yang mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Padahal jika dibandingkan dengan jumlah penyelenggaraan pilkada senasional, persentase terjadinya konflik sangat sedikit. Kalau pun terjadi konflik itu disebabkan elite partai dan pasangan calon yang tak menerima keterpilihan pasangan calon lain.
Pada konferensi pers “Mengecam dan Menolak Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD” yang diselenggarakan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (5/9), pakar pemilu, Sri Budi Eko Wardani mengatakan, alasan konflik tinggi di pilkada tak tepat. Direktur eksekutif Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) ini membandingkan jumlah pilkada se-Indonesia yang ternyata persentase terjadinya konflik sangat kecil. Konflik yang terjadi pun lebih berdasar para elite yang tak terpilih tak bisa menerima keterpilihan kandidat lain.
“Seharusnya perbaikan pemilu nasional dan daerah lebih banyak pada pembahasan perbaikan partai. Yang didorong harusnya reformasi partai untuk terbuka. Tertutupnya partai pun menjadikan biaya pilkada sangat fantasitis termasuk di dalamnya harga pencalonan kepala daerah di dalam partai atau koalisi partai,” jelas Sri.
Pakar tata negara, Refly Harun menilai soal konflik merupakan hal yang harusnya tak diselesaikan dengan cara tak lebih demokratis. Direktur eksekutif Correct ini menilai sikap DPR yang ingin mengembalikan pilkada langsung menjadi melalui DPRD sebagai permasalahan konstitusional bagi Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan otonomi daerah.
Refly menilai, rakyat yang berdaulat melalui pemilihan langsung semakin dewasa menyikapi hasil pemilu. Ia merujuk pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Menurutnya, jika elite partai dan paslon yang tak terpilih bisa menerima keterpilihan paslon lain, konflik horizontal tak akan besar bahkan tak ada.
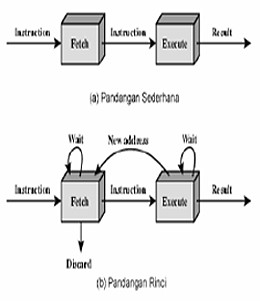
Komentar
Posting Komentar